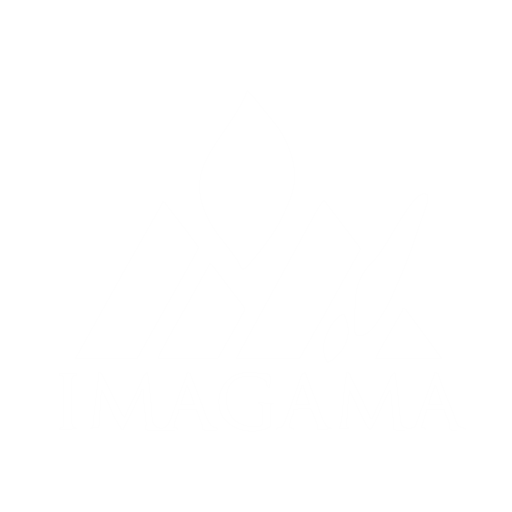Disusun oleh : Achmad Fauzi, Nathalie Anin, Erica Lesmana
Critical Audit Matters (CAM) merupakan pengungkapan masalah yang timbul dari hasil audit laporan keuangan yang dikomunikasikan atau perlu dikomunikasikan kepada komite audit berkaitan dengan akun atau pengungkapan yang material untuk laporan keuangan serta termasuk penilaian auditor yang menantang, subjektif, dan kompleks.
Kriteria yang dimiliki oleh suatu subjek sehingga dikatakan CAM setidaknya memenuhi 3 kriteria, yakni:
- Setiap materi yang muncul dari suatu audit laporan keuangan telah atau sepatutnya dikomunikasikan kepada komite audit.
Menurut AS 1301 “Communications with Audit Committees” hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan komite audit adalah: