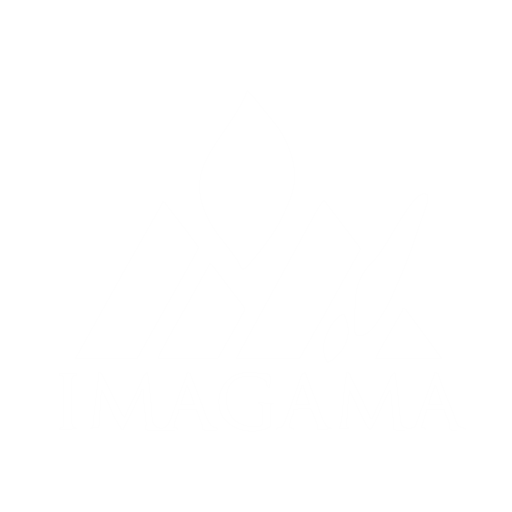Author: Nayla Phui Amazona; Editor: Farabiana Indira Pamungkas, Pijar Sahistya Mahiswara
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. AI telah dimanfaatkan di berbagai bidang, mulai dari proses otomasi industri, personalisasi layanan pelanggan, analisis pasar, hingga sistem keamanan digital yang canggih.